Agama adalah nafas hidup hampir seluruh penduduk bumi. Berdasarkan data The World Factbook CIA 2012, sekitar 90% penduduk dunia adalah pemeluk agama.Begitu juga dengan di Indonesia. Agama ada di setiap sendi kehidupan, dari rumah hingga ke gedung-gedung pemerintah, menjadi urat nadinya, penentu benar dan salah.
Ketika pertama kali menginjakkan kaki di
Amerika, saya bertanya-tanya ketika mengetahui bahwa di sini, antara
negara dan agama, dipisah. Kasarnya, negara tidak bisa ikut campur soal
agama warganya dan agama tidak bisa pula mengatur negara. Yang ada di
pikiran saya ketika itu, pasti bobrok sekali moral bangsa Amerika ini.
Pasti agama-agama minoritas, termasuk Islam, sangat tertindas di sini.
Namun, saya keliru.
Konstitusi Tanpa Tuhan & Agama
Jika dilihat dari demografi semata, Amerika bisa disebut sebagai negara relijius. Berdasarkan American Religious Identification Survey
(ARIS), sekitar 80% warganya adalah pemeluk agama, dengan 76% di
antaranya adalah pemeluk berbagai aliran Kristen Protestan (51%), serta
Katolik (25%). Sementara sisa 4% nya terdiri dari Yahudi (1.2%), Budha
dan berbagai agama dari Asia (0.9%), Islam (0.6%), serta agama-agama
lainnya (1.3%).

Namun, cukup mengejutkan ketika mengetahui
tidak ada satu pun kata “Tuhan” atau “Jesus” di konstitusi Amerika, yang
merupakan hukum tertinggi negara. Kata “agama” hanya muncul sekali, itu
pun sebagai penegas bahwa untuk menjadi anggota Kongres atau pejabat
publik seperti walikota, gubernur dan lain sebagainya, tidak boleh
menjadikan agama sebagai persyaratan.
Menarik untuk membayangkan bagaimana
Bapak-bapak Bangsa Amerika merancang konstitusi, lebih dari dua abad
lalu. Meskipun sebagian besar mereka diyakini memiliki kepercayaan sama,
yaitu Kristen, mereka berasal dari aliran dan sekte berbeda, dengan
gaya peribadatan yang berbeda pula. Para penyusun konstitusi ini ingin
memastikan, nantinya tidak ada satu agama atau aliran pun yang
mengontrol pemerintah.

Pemisahan negara dan agama diperkuat oleh surat balasan Presiden Thomas Jefferson kepada Gereja Danbury Baptist yang
merupakan aliran Kristen minoritas di Connecticut, pada tahun 1802.
Mereka merasa kebebasan beragama yang dinikmati saat itu, tidaklah
abadi, melainkan hanya hadiah basa-basi dari pemerintah negara bagian
belaka. Namun, Jefferson menegaskan :
“Kita sama-sama percaya bahwa agama
adalah urusan yang sangat pribadi antara manusia dan Tuhannya. Sehingga
para wakil rakyat tidak boleh membuat undang-undang yang mengatur
tentang keberadaan agama atau melarang kebebasan beragama. Ini berujung
pada adanya dinding pemisah antara negara dan agama.”
Apa pengaruhnya?
Dengan penegasan Jefferson, di
Amerika siapa pun berhak memeluk agama dan kepercayaan apapun yang
diyakininya atau tidak memeluk agama sama sekali. Siapapun tidak bisa
memaksa atau melarang orang lain untuk beragama atau beribadah.
Dari segi pemerintahan, tidak
ada Kementerian Agama di Amerika. Agama juga tidak pernah ditanyakan dan
dicantumkan pada kartu identitas, misalnya KTP, karena dinilai sebagai privacy.
Anggaran negara juga tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan agama.
Jadi, jika ada pembangunan gereja, mesjid atau sinagog, serta berbagai
acara keagamaan, pemerintah tidak boleh mendanainya. Pemerintah harus
netral.
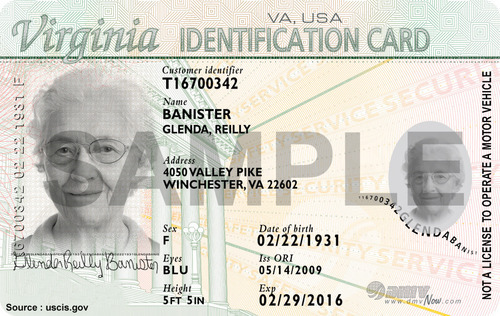
Selain itu, Konstitusi Pemisahan
Negara dan Agama melarang pemasangan patung dan simbol keagamaan di
kantor-kantor pemerintah. Meskipun begitu, individu atau tempat ibadah
tetap boleh memasangnya di rumah/gedung atau di halaman mereka.
Sementara, pemasangan simbol agama di tempat umum, dinilai ilegal.

Misalnya, akhir Desember lalu Pengadilan Federal Amerika memutuskan untuk memindahkan Mount Soledad Cross, sebuah salib setinggi hampir 13 meter dari Gunung Soledad, San Diego, California, yang semula didirikan sebagai monumen peringatan untuk veteran Perang Korea. Keputusan ini diambil setelah kontroversi terus memanas, terutama dari kelompok Ateis, yang menilai pemasangan salib di tempat umum menunjukkan keberpihakan pemerintah pada kelompok tertentu.
Saya tambah terkejut ketika
mengetahui ternyata agama tidak diajarkan di sekolah negeri di Amerika.
Bahkan, memaksa untuk berdoa atau beribadah bersama di sekolah, dianggap
mencederai hak asasi siswa yang tidak ingin melakukannya atau yang
meyakini cara lain untuk beribadah.
Semua ini didasarkan pada fakta
bahwa 90% anak Amerika menuntut ilmu di sekolah negeri. Mereka berasal
dari keluarga dengan latarbelakang agama dan kepercayaan yang berbeda.
Tidak ikut serta mengatur pendidikan agama, adalah salah satu cara yang
bisa dilakukan sekolah untuk menghormati agama dan kepercayaan setiap
anak, serta melindungi hak orang tuanya.
Sulitkah Beribadah?
Meskipun terdapat tembok pemisah antara
negara dan agama, di sisi lain, kebebasan beragama sangat dijunjung.
Pelajaran agama bisa didapat dengan bebas di berbagai tempat ibadah.
Tidak sedikit pula orang tua yang memasukkan anaknya ke sekolah swasta
berbasis agama, seperti sekolah Katolik, Yahudi atau Islam.
Nilai-nilai agama juga bisa diperoleh dari
berbagai organisasi. Misalnya, untuk Muslim Indonesia di Washington,
D.C. Area, bisa belajar tentang Islam, belajar mengaji, melaksanakan
Sholat berjamaah, atau ikut pesantren kilat saat bulan Ramadan, bersama
organisasi IMAAM (Indonesian Muslim Association in America) yang telah
berdiri sejak lebih dari 20 tahun lalu.


Karena kebebasan beragama ini pula, pegawai
negeri Amerika, bahkan tetap bisa beribadah di kantornya. Di kantor VOA
Indonesian Service di Washington, D.C. yang merupakan instansi
pemerintah Amerika, terdapat Mushola tempat para karyawan Muslim
beribadah.
Mushola ini dulunya adalah gudang, yang
kemudian disepakati untuk dijadikan tempat Sholat. Para karyawan
Indonesia kemudian memasang karpet dan sajadah di ruang ini. Selain itu,
setiap Jumat-nya, karyawan Muslim dari seluruh servis bahasa juga bisa
menggunakan aula kantor VOA sebagai tempat pelaksanaan Sholat Jumat
bersama. Saat perayaan Idul Fitri, karyawan juga dipersilahkan untuk
cuti atau masuk setengah hari agar bisa melaksanakan Sholat Ied paginya.

Siswa sekolah negeri juga dibolehkan untuk
beribadah di sekolah. Misalnya saja, jika diminta, guru-guru SMA di
Negara Bagian Virginia dan Maryland, selalu memberi izin kepada siswa
Indonesia untuk Sholat Dzuhur atau Ashar di sekolah, bahkan saat proses
belajar-mengajar berlangsung. Mereka Sholat di ruangan yang tidak
terpakai atau perpustakaan sekolah. Tidak hanya itu, saat bulan Ramadan
mereka dipersilahkan untuk tidak mengikuti kelas olahraga.
Intinya, asal dilaksanakan individu atau
kelompok secara sukarela, tanpa paksaan, tidak membahayakan orang lain,
serta tidak dibiayai dan tidak diatur oleh negara, kegiatan agama di
instansi pemerintah, dipersilahkan.
“Orang sini (Amerika) mah, gak akan berani melarang-larang orang beribadah,”
kata seorang Ibu asal Indonesia yang telah lebih dari 15 tahun tinggal
di Amerika dan mempunyai dua anak yang bersekolah di Virginia.
Kisah Semu Terpinggirkannya Islam
Sejak kecil saya sering mendengar betapa
Amerika disebut sebagai negara yang membenci Islam. Apapun akan
dilakukan negara ini untuk meruntuhkan Islam. Siapapun yang datang akan
dicuci otaknya dan dijadikan kafir. Namun, berhari-hari, berbulan-bulan,
bahkan sudah nyaris setahun menghirup udara Amerika, saya tidak bisa
membuktikan tuduhan itu. Yang terjadi justru sebaliknya.
Setelah tragedi 11 September, Islam, yang merupakan minoritas, justru menjadi agama yang paling pesat perkembangannya di Amerika. Berdasarkan Association of Religious Data Archives,
sepuluh tahun sejak tragedi yang menewaskan lebih dari tiga ribu orang
tersebut, jumlah pemeluk Islam di Amerika meningkat 66%, dari 1.5 juta
pada tahun 2001 menjadi 2.6 juta orang tahun 2011 lalu. Kemana pun
pergi, mulai dari New York, Los Angeles, Miami, bahkan Las Vegas, Muslim
dan perempuan berhijab bukan hal yang janggal untuk ditemui.

Walaupun begitu, tidak bisa dipungkiri tragedi 11 September sempat menyulut sentimen negatif terhadap Islam.
Misalnya rencana pembakaran Al-Quran oleh Pastur Terry Jones di Florida, pada peringatan sembilan tahun serangan 11 September,
2010 silam. Secara hukum, dia dilindungi hak kebebasan dalam
berekspresi. Namun, meski antara negara dan agama dipisah, sebelum Terry
melaksanakan aksinya, pemerintah tetap memberi himbauan.
Menteri Luar Negeri saat itu,
Hillary Clinton, menyayangkan aksi Terry yang disebutnya sebagai
penghinaan yang memalukan. Presiden Barack Obama bahkan menegaskan
rencana Terry bisa menyulut kekerasan di berbagai penjuru dunia.
Alhasil, sang Pastur mengurungkan niatnya.
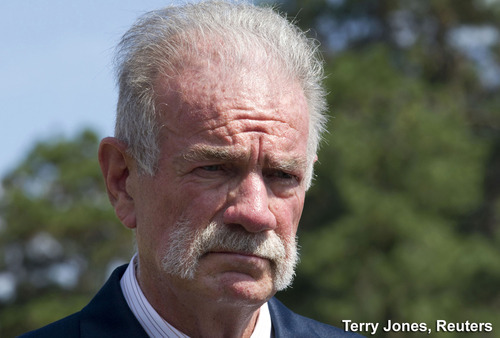
April 2013, Terry ditahan dengan tuduhan membawa bahan bakar dan senjata api secara tidak sah di tempat umum, saat berencana membakar 2998 Al-Quran, jumlah yang sama dengan korban tragedi 11 September. Walaupun bebas berekspresi, jika berpotensi mengganggu keamanan dan berujung kriminal, aparat berhak menindak.
Kontroversi juga sempat menyelimuti pembangunan Islamic Community Center, dua blok dari bekas tempat berdirinya World Trade Center, beberapa waktu lalu.
Sebagian besar pihak yang kontra, tidak mempermasalahkan Islam dan
kegiatan agama yang akan dilakukan di sana. Mereka mempermasalahkan
pemilihan lokasi yang dinilai kurang sensitif terhadap keluarga korban.
Mengapa harus sangat dekat dengan Ground Zero?
Namun, kontroversi hanyalah kontroversi.
Pemikiran bebas diutarakan. Meskipun tahun 2010 unjuk rasa penolakan
terus terjadi, pembentukan Islamic Community Center tetap berlanjut karena hukum melindunginya, melindungi kebebasan beragama. Apalagi Presiden Obama menegaskan :
“Adanya hak bagi siapapun untuk membangun tempat ibadah di properti milik pribadi di lower Manhattan.”
Alhasil, September 2011 lalu, pusat komunitas
Muslim yang kontroversial tersebut telah menyelenggarakan acara besar
perdananya, yaitu pameran foto anak-anak dari berbagai penjuru dunia.

Ketika berkunjung ke New York beberapa waktu lalu, saya sempat mendatangi Islamic Center
tersebut. Lantai dasar, yang merupakan lokasi utama berbagai aktivitas,
terdiri dari dua bagian ; ruang bercat putih tempat sejumlah kegiatan
budaya dilaksanakan, serta ruang Sholat yang bisa menampung lebih dari
250 jamaah. Sementara, tempat Wudhu terdapat di basement. Meskipun tidak banyak, siang itu saya melihat Muslim dari berbagai ras berdatangan dan melaksanakan Sholat Dzuhur berjamaah.



Berkembangnya Islam di Amerika juga bisa
dilihat dari keberadaan Mesjid. Saat berkunjung ke berbagai negara
bagian di Amerika, saya selalu bisa menemukan Mesjid atau setidaknya
Mushola. Ini sejalan dengan hasil penelitian Hartford Institute of Religion Research tahun
2011 yang menyatakan sejak tahun 2000, jumlah Mesjid di Amerika naik
74%. Setidaknya terdapat 900 mesjid baru dengan total lebih dari 2100
Mesjid di Amerika. Sebagian besar terletak di kota besar.
Namun, seiring bertambahnya warga yang hidup
di daerah pinggiran kota, keberadaan Mesjid juga semakin menyebar. Salah
satunya, sedang diusahakan oleh Pak Kustim Wibowo, seorang dosen asal
Indonesia di Indiana University, Pennsylvania. Lahan untuk
Mesjid seluas 6.000 meter persegi seharga $48.000, diperoleh Pak Kustim
dan rekan-rekannya tanpa masalah. Kini mereka sedang mengumpulkan dana
agar rumah ibadah tersebut dapat segera dibangun.

Yang sama sekali tidak pernah saya bayangkan
adalah hal serupa, bahkan terjadi di negara bagian paling relijius di
Amerika, dengan 60% penduduknya beragama Mormon, yaitu Utah. Setidaknya
terdapat 5 Mesjid di ibukota Utah, Salt Lake City, yang dikelilingi
lekuk-lekuk cantiknya pegunungan.
Saya semakin tersentuh mendengar cerita Pak
Heru Hendarto, lelaki asal Indonesia yang menjadi tokoh masyarakat Asia
di Salt Lake City. Ketika menjadi Presiden Muslim Student Organization (MSO) di University of Utah (U
of U) tahun 1997-1999 silam, Ia menuliskan keluhannya di jurnal
mahasiswa tentang kesulitan mahasiswa Muslim mendapatkan ruangan untuk
Sholat Jumat. Padahal saat itu organisasi Kristen, Mormon, Yahudi bahkan
Budha, mendapat perhatian kampus.
Membaca tulisan tersebut, Presiden U of U dan
Ketua Senat langsung memanggil Pak Heru untuk menanyakan apa yang bisa
dibantu. Setelahnya, setiap Jumat, satu ruang kuliah, sepanjang tahun
disediakan khusus untuk MSO.

“Di sini masalah agama bagus kok. Orang
tidak mau ada isu soal diskriminasi agama. Salah satu Mesjid di Salt
Lake City, tanahnya bahkan disumbangkan oleh Gubernur Utah.” Ujar Pak Heru. Saya hanya bisa terdiam.
Bahkan, Ahmadiyah yang mendapat diskriminasi di Indonesia,
berkembang pesat di Amerika. Di Mesjid mereka yang megah di Silver
Spring, Maryland, saya terenyuh melihat bagaimana para jamaah bisa
bersujud tanpa mendengar hujatan, tanpa disergap ketakutan.

“Di berbagai tempat di dunia, kami tidak
dianggap. Namun di sini, hak dasar kemanusiaan kami untuk mempraktikkan
agama, tidak pernah direbut,” ungkap Wakil Presiden
Komunitas Ahmadiyah Amerika, Naseem Mahdi dengan suara bergetar. Saya
terenyuh dengan berbagai fakta, malu terhadap stigma semu yang pernah
saya yakini tentang Amerika.
Ironi Negeri di Jantung Khatulistiwa
Awal 2014, saya menelpon orang tua di kampung
halaman di Sumatera. Pembicaraan kami santai seperti biasa sampai ayah
saya bercerita tentang berita yang baru dibacanya di koran : Wali Kota
membatalkan rencana pembangunan sebuah rumah sakit dan sekolah di Kota
Padang, Sumatera Barat. Salah satu alasan utamanya adalah karena protes
warga bahwa proyek yang direncanakan Pemkot bersama sebuah grup
konglomerasi besar yang berasal dari etnis dan agama minoritas tersebut,
nantinya dikhawatirkan masyarakat, akan merusak akidah mereka. Hati
saya mencelos mendengarnya.
Di saat percakapan dengan ayah terus
berlanjut, ingatan saya terbang secepat kilat, kembali ke beberapa
penugasan liputan sebelum berangkat ke Amerika. Saya masih ingat berada
di dalam sebuah Mesjid milik jamaah Ahmadiyah di Sindang Barang, Bogor,
Jawa Barat. Satu-satunya Mesjid yang menerima saya dan tim liputan,
setelah seharian ditolak berbagai komunitas Ahmadiyah di Bogor karena
mereka ketakutan, kedatangan kami untuk meliput dampak konflik komunal
di tanah air, akan memicu kemarahan warga. Di dalam Mesjid yang pernah
disegel Pemkot Bogor dan tidak lagi memiliki plang nama itu, para jamaah
mengungkapkan harapan mereka, yang semuanya hampir sama : keamanan,
ketentraman dan kebebasan dalam beribadah.


Teriakan puluhan orang di tanggal 25 Desember
2011, juga kembali terngiang di telinga. Mereka menghadang puluhan
jemaat GKI Yasmin, Bogor, yang sedang menuju Gereja untuk melaksanakan
Misa Natal.
Pagi itu, ratusan aparat kepolisian
memblokade setiap jalan untuk menuju Gereja GKI Yasmin, yang izinnya
telah dimenangkan oleh Mahkamah Agung. Puluhan orang yang tadi
berteriak-teriak, lalu menyebut-nyebut nama Tuhan sambil mengusir para
Jemaat menjauh dari barikade polisi, yang tentunya tidak akan bisa
dilewati. Tercekat rasanya mengingat kejadian itu.
Memori peristiwa-peristiwa serupa terus berganti di benak, bagai roll-film
yang diproyeksikan ke layar bioskop: Pembakaran rumah dan penyerangan
terhadap kelompok Islam Syiah di Sampang, Madura, Agustus 2012,
Penyegelan, penutupan dan bahkan pembongkaran berbagai Gereja di tanah
air dengan dalih tidak adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB),
Penyerangan yang mengakibatkan tewasnya tiga penganut Ahmadiyah di
Cikeusik, Bogor, Februari 2011, dan masih banyak kejadian menyedihkan
lainnya.

Ironis sekali, ternyata di negara saya
sendiri lah, di tempat yang mengakarkan berbagai sisi kehidupan pada
agama, dengan Ketuhanan yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan
Beradab sebagai bagian ideologinya, dengan kebebasan beragama yang
dijamin oleh konstitusinya, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan
negara, serta Kementerian Agama untuk membina kerukunan umatnya,
toleransi dan bahkan kebebasan untuk menjalankan agama, justru masih
menjadi barang mewah yang sulit didapatkan.
Pemerintah seakan menjadi wakil dan milik
kelompok mayoritas, yang bergerak dengan pemikiran mayoritas pula.
Minoritas dilihatnya menakutkan, dianggap sebagai kelompok pendosa yang
layak dibasmi karena dinilai menjadi racun pengancam keberadaan
mayoritas.
Saya malu, karena saya sendiri pernah tumbuh
dengan pemikiran itu. Saya tumbuh melihat orang dengan agama berbeda
sebagai makhluk asing yang sewaktu-waktu bisa mencelakakan, sehingga
kewaspadaan dan jarak harus tetap dijaga.
Apakah ini karena saya dan banyak dari kita
dididik sedari kecil, di berbagai tempat pendidikan, ditanamkan
pemikiran yang kemudian larut di alam bawah sadar bahwa hanya kita lah
yang benar, agama kita lah yang paling benar, sementara agama berbeda
itu salah, menyesatkan dan tidak dapat diterima?
Memang, itulah kepercayaan. Namun, apakah ini
membuat kita terlena, larut memaknai agama sebatas betapa benarnya
keyakinan kita dan betapa salahnya keyakinan yang berbeda? Bukankah di
mata orang dengan keyakinan berbeda, keyakinan kita lah yang salah dan
mereka lah yang benar?
Mengapa kita menggunakan fakta mayoritas kita
untuk mendiskriminasi mereka dan merebut hak mereka? Mengapa kita tidak
bisa menerima perbedaan ini dan menjadikan agama urusan paling pribadi
antara individu dengan Tuhan, tanpa perlu memperdebatkannya, tanpa perlu
menyakiti orang lain?
Memang tidak pantas untuk
membanding-bandingkan Indonesia dengan Amerika. Masing-masing punya
catatan baik dan buruk tentang toleransi beragama. Apalagi saya baru
tinggal setahun di sini. Masih sangat banyak hal yang belum saya lihat,
tempat yang belum saya kunjungi.
Namun, sebagai orang yang tumbuh di tanah air
dengan stigma betapa kejamnya Amerika memperlakukan orang-orang
beragama minoritas, betapa Amerika kerap dituding akan akal busuk dan
kekafirannya, saya merasa perlu untuk menyampaikan bahwa apa yang saya
lihat dan rasakan selama ini di Amerika, justru sebaliknya, toleransi
lah yang ada, tepa selira lah yang terasa.
Menjadi pemeluk agama minoritas, bukan berarti menjadi alasan untuk tidak dihargai. Mayoritas bukan berarti berkuasa untuk menindas.
Ironis, ini bukan terjadi di sebuah negara
di jantung khatulistiwa, yang menjadikan agama sebagai akar hidupnya.
Ini justru terjadi di sebuah negara yang seakan agama dibungkam tapi
sebenarnya dimerdekakan, di sebuah negara yang moralnya kerap dipandang
sebelah mata, di sebuah negara yang seakan hidup tanpa agama. ()
Tidak ada komentar:
Posting Komentar